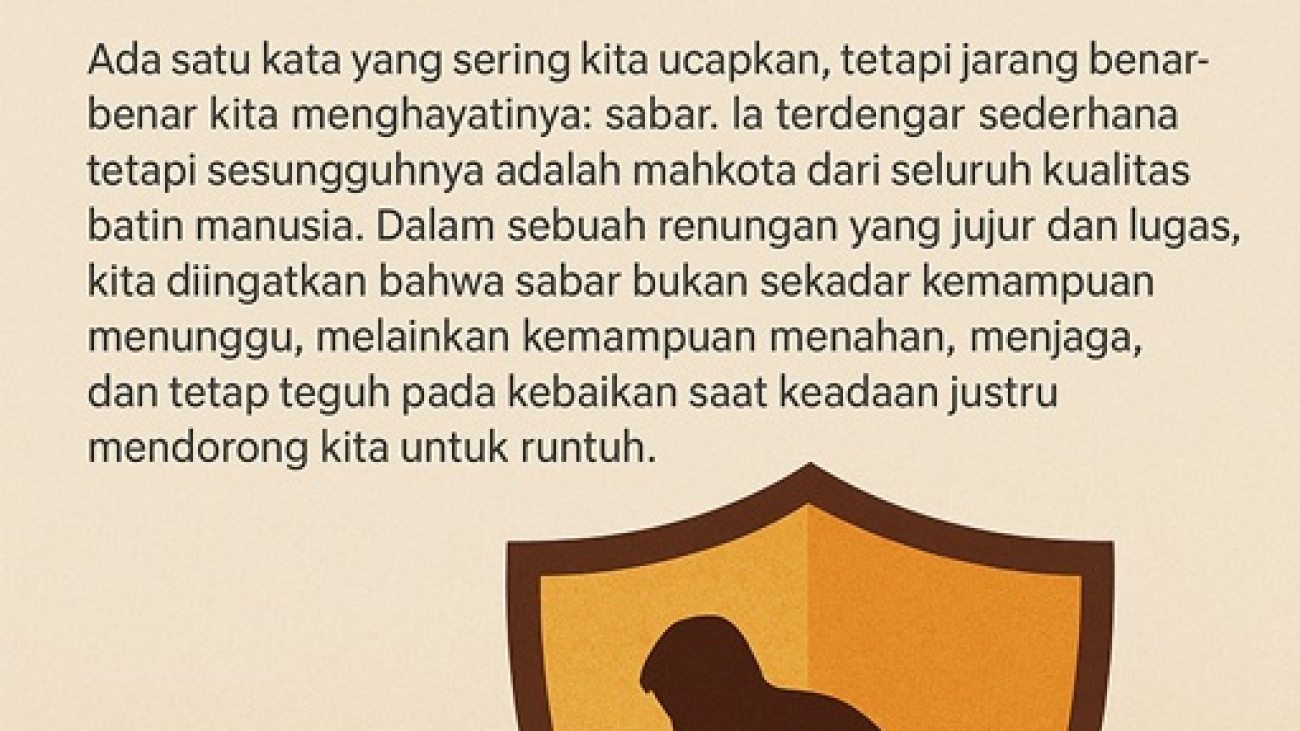Menyambut tahun 2026 Sekolah Bakti Mulya (BM) 400 kembali melaksanakan kegiatan kick off meeting pada hari Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini dirancang sebagai momentum konsolidasi nilai, kebijakan, dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kian menantang. Hadir seluruh guru BM 400 dan pimpinan sekolah meneguhkan arah di tahun 2026.
Acara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB itu menjadi penanda dimulainya fase baru pengelolaan pendidikan Bakti Mulya 400. Bukan hanya evaluasi capaian 2025, tetapi juga penegasan one year policy 2026 yang menuntut disiplin eksekusi dan kesatuan visi di seluruh unit sekolah—Jakarta, Cibubur, hingga Depok yang baru bergabung dalam keluarga besar Bakti Mulya 400.
Kick Off ini terasa istimewa karena menghadirkan dua pemikir publik terkemuka: Prof. Komaruddin Hidayat dan Prof. Yudi Latif. Keduanya hadir bukan sebagai pembicara motivasional, melainkan sebagai peneguh fondasi etis kepemimpinan pendidikan. Diskusi panel bertajuk “The Leadership: Guiding with Faith and Purpose” menjadi ruang refleksi kolektif tentang kepemimpinan yang tidak berhenti pada target administratif, tetapi berpijak pada iman, nilai, dan tujuan jangka panjang.
Dalam laporannya, Deputi KPH/Chief Operating Officer Bakti Mulya 400, Euis Tresna, M.Si. memaparkan capaian strategis tahun 2025 sekaligus peta jalan kebijakan 2026. Ia menekankan pentingnya konsistensi tata kelola, penguatan sumber daya manusia, dan keberlanjutan program yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Sejumlah capaian diapresiasi, termasuk penghargaan purnabakti, penguatan status guru tetap, guru terbaik, sertifikasi pendidik, hingga program apresiasi ibadah umrah bagi guru.
Ketua Pelaksana Harian/CEO Bakti Mulya 400, Dr. Sutrisno Muslimin, M.Si. dalam sesi pembinaan menegaskan bahwa sekolah tidak boleh kehilangan orientasi nilai di tengah tekanan kinerja. Tahun 2026 adalah fase konsolidasi strategis untuk memperkuat tata kelola, mutu, dan keberlanjutan pendidikan. Berlandaskan tiga pilar—religius, nasionalis, dan internasional—BM 400 diarahkan menjadi sekolah bernilai yang dikelola secara profesional dan berbasis sistem.





“Bakti Mulya 400 tidak sekadar ingin menjadi sekolah unggul di tingkat nasional, tetapi berikhtiar menjadi sekolah dunia—berstandar internasional, berakar pada nilai keislaman, dan berpijak teguh pada kebangsaan”, tegas Sutrisno Muslimin.
Puncak simbolik acara ini adalah penandatanganan Komitmen Capaian Sekolah Bakti Mulya 400 Tahun 2026. Para kepala unit, pimpinan divisi, hingga jajaran manajemen menandatangani dokumen komitmen sebagai pernyataan tanggung jawab bersama. Komitmen itu dipertegas dengan penandatanganan Business Plan Sekolah Bakti Mulya 400 Depok 2026–2031 bersama Ketua Yayasan Amanah Cerdas Bangsa, Ibu Tejaningsih Haiti—menandai fase ekspansi yang diikat oleh tata kelola dan visi yang sama.
Nuansa kebangsaan terasa kental saat untuk pertama kalinya Hymne Bakti Mulya 400 dikumandangkan. Lagu itu bukan sekadar simbol institusi, melainkan penanda identitas kolektif sekolah yang menempatkan pendidikan sebagai kerja nilai dan kebudayaan.
Diskusi panel yang berlangsung hingga siang hari menjadi ruang kontemplatif. Prof. Komaruddin Hidayat mengajak para pendidik kembali pada kepemimpinan batin—kepemimpinan yang dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Sementara Prof. Yudi Latif menegaskan pentingnya moral purpose dalam pendidikan: sekolah harus menjadi ruang pembentukan warga negara yang berkarakter, bukan sekadar penghasil lulusan.
Baca juga : Menemukan Moral Purpose di Medan Pendidikan
Pesan itu dipertegas secara simbolis melalui penyerahan buku karya Yudi Latif, “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia”, kepada sembilan guru perwakilan. Buku tersebut akan digunakan sebagai praktik baik penguatan pendidikan kebangsaan di Bakti Mulya 400—sebuah langkah kecil yang diharapkan memberi gema panjang dalam ruang kelas.
Pada akhirnya, Kick Off 2026 bukan sekadar penanda pergantian tahun kerja, melainkan pernyataan sikap. Bakti Mulya 400 memilih bertumbuh tanpa kehilangan nilai, maju tanpa tercerabut dari akar. Sekolah ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah, pembelajaran adalah kerja peradaban, dan masa depan tidak dibangun oleh kecepatan semata, melainkan oleh arah yang benar. Tahun 2026 pun dibuka dengan satu ikrar —melangkah ke dunia, sambil tetap setia pada iman, kebangsaan, dan martabat manusia.